FILM SEBAGAI MEDIA PENCITRAAN DAERAH[1]
Oleh
Emeraldy Chatra[2]
Film telah membuat citra seniman daerah sebagai orang-orang tolol di dunia film, dan membuat citra sineas Jakarta serba lebih hebat.
Ketika kita menonton film-film buatan Bollywood yang muncul ke hadapan kita adalah wajah India, bukan wajah Mumbay atau New Delhi. Begitu juga ketika kita menonton film-film produksi Hollywood (Amerika Serikat), yang kita lihat adalah wajah negara Paman Sam itu, bukan wajah Los Angeles atau Washington. Tapi ketika kita menonton film-film buatan Indonesia yang terlihat adalah wajah Jakarta dan sekitarnya (Bogor atau Bandung), mulai dari yang sangat glamor dan berkelimpahmewahan sampai pada suasana perkampungan yang paling jorok.
Terpusatnya industri film di Jakarta menyebabkan film Indonesia didominasi oleh film-film yang menjadikan kehidupan metropolitan sebagai setting cerita. Wajah Jakarta dan sekitarnya jauh lebih tampak dibandingkan wajah daerah-daerah lain di luar daerah tsb. Wajah Jakarta itulah yang dipaksakan sebagai wajah Indonesia, seolah-olah Indonesia merupakan sebuah negara kota yang sangat urban. Padahal, Indonesia bukanlah Jakarta plus Bogor plus Bandung. Lebih kurang 80% rakyat Indonesia hidup di luar Jakarta, di daerah-daerah perdesaan yang kebanyakan masih mempertahankan tradisinya yang eksotis. Dengan kondisi seperti itu film kita lebih tepat dikatakan film Jakarta daripada film nasional.
Tampaknya, daerah-daerah di luar Jakarta, terutama Sumatra, Kalimantan, Sulawesi atau Papua tidak dianggap memberi nilai tambah kepada film oleh para industrialis maupun seniman film yang hampir seluruhnya berdomisili di Jakarta. Agaknya mereka berpikir, jika bisa membuat film yang menguntungkan di Jakarta atau kota-kota di sekitarnya, mengapa harus repot-repot datang ke kota-kota atau nagari-nagari di Sumatera Barat atau paserah di Sumatera Selatan? Mengapa pula harus membuang uang banyak untuk datang ke Papua, sementara filmnya belum tentu laris di pasar?
Alasan seperti itu tentu sangat logis, karena film adalah produk industri padat modal yang rentan rugi. Lagi pula, kebanyakan rakyat Indonesia tidak pernah mempersoalkan dimana sebuah film dibuat. Mereka tidak pernah memprotes mengapa industri film sejak dulu hanya di Jakarta, tidak pernah tampak tanda-tanda akan bergerak ke luar Jakarta. Tidak banyak yang membandingkan industri film India yang tidak berpusat di New Delhi, tapi di Mumbay, atau industri film Amerika Serikat tidak di Washington, tapi di Los Angeles.
Tak ayal, pemusatan industri film di Jakarta menimbulkan mitos dan anggapan bahwa yang bisa membuat film hanya orang Jakarta. Orang-orang daerah tidak sepandai orang Jakarta; kalau membuat film tanpa bantuan orang Jakarta pasti jelek, pengusaha daerah tidak mengerti film, artis daerah tidak ada yang berbakat, dan sebagainya.
Sebagian anggapan itu tidak salah. Di Jakarta ada IKJ (Institut Kesenian Jakarta) yang mengajarkan bagaimana membuat film dan telah menghasilkan sineas-sineas terkemuka. Mereka umumnya mencari hidup di Jakarta setelah menamatkan pendidikan. Sebagian memang kembali ke daerah dan tak pernah menjadi sineas terkemuka di tingkat nasional.
Di samping itu, di Jakarta juga jauh lebih mudah mendapatkan dana untuk memproduksi film, penyewaan peralatan tersedia, studio-studio canggih juga ada. Semua itu, harus jujur diakui, sukar diperoleh di daerah. Berbagai kesulitan yang dihadapi seniman daerah dalam usaha mereka menghadirkan film yang layak tonton akhirnya membangun citra bahwa di daerah hanya ada penonton, tidak ada seniman yang mampu membuat film.
Pertanyaan kita, sampai kapan masyarakat daerah melulu harus menjadi konsumen film-film Jakarta? Kapan citra ‘tidak melek film’ yang melekat pada seniman daerah berubah menjadi ‘melek film’? Kapan berbagai kearifan lokal yang masih subur di Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi dapat dihadirkan oleh sineas daerah untuk dikonsumsi oleh orang-orang Jakarta? Atau, secara ekonomis, kapan orang daerah dapat menyedot uang orang Jakarta dari industri film mereka setelah sejak dulu kala hanya menyetor uang – dengan menonton -- kepada industri film Jakarta?
Dalam penilaian saya, dunia film bukanlah dunia yang tidak dapat dijangkau oleh para seniman daerah. Seniman daerah tidak perlu merasa rendah diri berhadapan dengan seniman Jakarta yang dibesarkan oleh fasilitas, tapi nyatanya juga tidak terlalu hebat dibandingkan seniman film India, Hongkong, apalagi Amerika Serikat. Toh karya-karya film-maker Jakarta hingga hari ini tetap tidak dikenal di dunia internasional, kendati satu dua sudah mendapatkan penghargaan di festival Cannes. Singkatnya, sineas Jakarta belum naik ke langit ke tujuh sehingga tidak dapat lagi dikejar oleh para seniman daerah. Mereka masih satu dua langkah saja di depan.
Justru dalam pikiran saya seniman daerah dapat menjadi lebih tegar, tidak manja dan dinamis mengingat demikian besarnya tantangan untuk berkarya. Berbagai kesulitan yang tidak dialami sineas Jakarta, tapi umum dialami oleh seniman lokal, dapat menjadi sumber inspirasi untuk membangun strategi berkarya yang lebih baik atau lebih efisien. Yang penting, jangan pernah ada istilah patah semangat, karena itu merupakan virus pembunuh utama bagi kegiatan kesenian apapun.
Apakah Orang Sumatera Barat bisa Bikin Film?
Hanya orang-orang yang tidak tahu sejarah yang akan mempertanyakan kemampuan orang Sumatera Barat membuat film. Baru saja Indonesia merdeka, orang Sumatera Barat sudah muncul sebagai tokoh-tokoh legendaris di dunia film. Mereka adalah Anjar Asmara, Usmar Ismail, Djamaludin Malik, Dr Abu Hanifah, dan Drs. Asrul Sani. Tokoh lain yang berasal dari Sumatra Barat adalah Roestam St. Palindih dan Dr Adnan Kapau Gani. Namun malangnya mereka kemudian lebih dikenal sebagai orang Jakarta, dan nama mereka tidak banyak dikenal di Sumatera Barat. Semangat mereka juga tidak menular ke dada seniman daerah yang terperangkap oleh mitos rendah diri karena tinggal jauh dari pusat kekuasaan.
Kini usaha-usaha seniman Sumatera Barat untuk mengikuti jejak pendahulu mereka di dunia film tanpa harus hijrah ke Jakarta sudah mulai menggeliat. Hal ini muncul sejalan dengan makin murahnya peralatan produksi seperti kamera dan komputer editing. Paling tidak seniman daerah Sumatera Barat sudah menghasilkan sinetron-sinetron lepas dan video dokumenter yang dikemas dalam CD kemudian ditayangkan dalam acara-acara sederhana. Untuk hadir di televisi memang masih memerlukan perjuangan panjang, kendati di Padang dan Bukittinggi sudah berdiri stasiun televisi lokal.
Langkah maju ke industri film juga masih tersendat. Mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang perfilman belum lagi jadi pilihan pengusaha daerah. Undang-Undang Perfilman No. 8/1992 dan PP No. 6/1994 yang dianggap sebagai pembunuh kreativitas insan perfilman, sekalipun tidak lagi efektif, tetap jadi hantu karena bagi pemilik modal karena belum dicabut. Undang-undang dan peraturan produk Orde Baru ini merupakan manifestasi kezaliman sebuah rejim terhadap kebebasan berkreasi dan berusaha di sektor perfilman karena menetapkan berbagai aturan dan larangan yang seolah-olah meletakkan sebelah kaki para sineas selalu dalam penjara. Di sisi lain, Undang-undang dan peraturan ini seakan meletakkan para pengusaha di pintu lembaga-lembaga Pemerintah yang diduduki para koruptor, sehingga para pengusaha setiap saat dicekik oleh ongkos perizinan dan biaya-biaya ekstra yang memangkas laba usaha sebelum produksi berjalan.
Tanpa pencabutan UU No.8/1992 dan PP No.6/1994, kreativitas seniman daerah mungkin tetap dapat berjalan, tapi pasti sangat tersendat-sendat. Sejauh ini tampaknya Pemerintah RI masih belum punya goodwill yang cukup tinggi untuk mencabut dan menggantinya dengan aturan yuridis yang lebih memerdekakan industri perfilman. Usulan-usulan perubahan yang dikemukakan insan perfilman masih terlihat seperti buih di tengah lautan. Padahal, kalau industri perfilman telah merdeka dari cengkraman aturan yang represif pengusaha Sumatera Barat yang bermodal kecil sekalipun akan dapat masuk ke industri sinetron dalam skala usaha rumah tangga. Artinya, di alam kemerdekaan membuat film para seniman daerah tidak perlu menunggu investor luar bermodal puluhan miliar. Dengan modal Rp 150 juta saja seorang pengusaha sudah dapat memulai kegiatannya. Menurut kebiasaan, investor kakap akan melirik dengan sendirinya bila telah mencium adanya keuntungan di balik kegairahan masyarakat berproduksi.
Di tingkat lokal keinginan pemerintah di daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota di Sumatera Barat, untuk mendesak Pemerintah RI agar melonggarkan tekanan terhadap industri film dan agar lebih memperhatikan perfilman daerah belum tampak sama sekali. Hal ini mungkin disebabkan selama ini persentuhan Sumatera Barat dengan dunia film baru sebatas menonton dan ikut-ikutan jadi pemain kalau ada yang datang untuk shooting. Agaknya pula pemerintah di Sumatera Barat belum sepenuhnya memperhatikan pergeseran-pergeseran dalam paradigma industri, dimana industri media audio visual makin memperlihatkan kekuatannya sebagai penyedia lapangan kerja, pendidikan masyarakat, bahkan penghasil devisa.
Oleh sebab itu, keterlibatan institusi pemerintah di Sumatera Barat, mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten, termasuk juga kalangan wakil rakyat di DPRD dalam memperjuangkan kebebasan industri film sangat diharapkan. Pemerintah RI harus didesak terus agar membiarkan industri perfilman daerah tumbuh secara alamiah tanpa dibebani berbagai kewajiban politik, ekonomi dan administratif yang sukar dipenuhi oleh pengusaha daerah. Bukankah di daerah seperti Sumatera Barat umumnya golongan pengusaha baru berada pada kelas kecil dan menengah?
Dengan adanya atmosfir kebebasan, kita berharap, suatu saat nanti citra ‘tidak melek film’ tidak lagi melekat pada diri seniman Sumatera Barat. Untuk itu harus ada upaya ekstra keras membangun citra sebagai sineas yang ulet, kreatif, tidak manja, dan tidak dibesarkan oleh fasilitas.
Sekian.
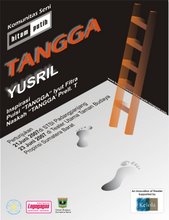

No comments:
Post a Comment